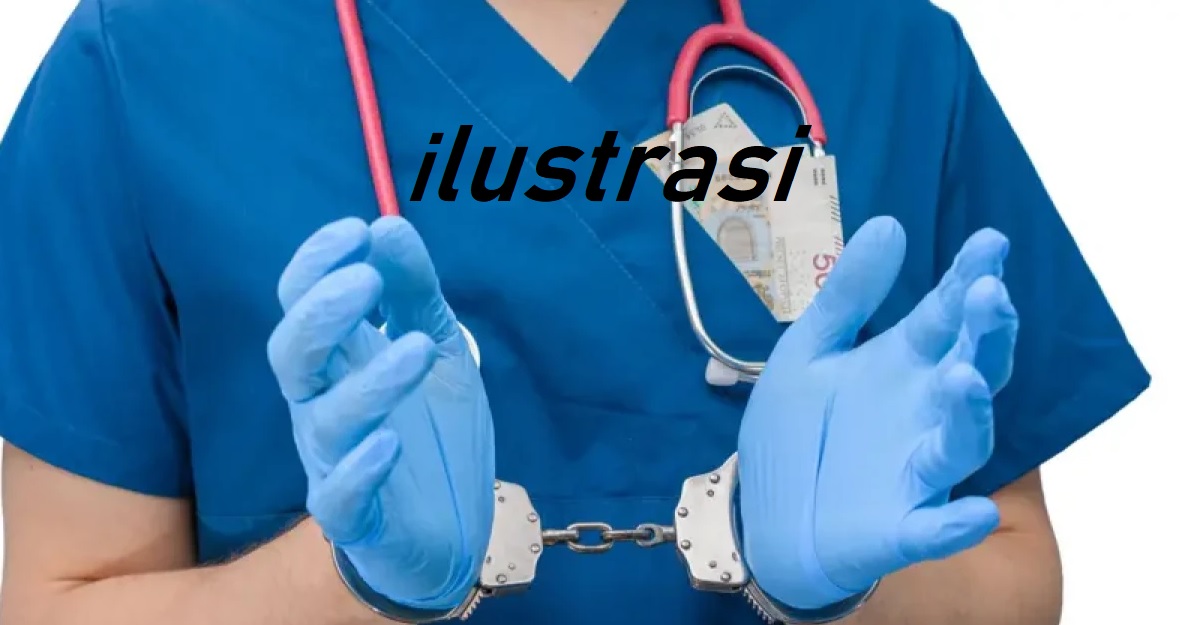
5 Solusi dari Kasus Kekerasan Seksual di Ruang Medis
Oleh : Ahmad Muhamad Mustain Nasoha
( Dosen Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Tarbiyah, UIN Surakarta dan Direktur PUSKOHIS )

Peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Tenaga Medis terhadap Pengguna Layanan Kesehatan menegaskan kembali urgensi pembenahan sistemik dalam sektor Pelayanan Publik. Perbuatan tersebut tidak hanya masuk dalam kategori Sexual Criminal Offense (Delik Kesusilaan) yang berat, tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam penerapan prinsip Due Process Of Law (Prosedur Hukum Yang Adil dan Dijamin Konstitusi) dalam konteks penegakan etik profesional.
Ketika Pelaku memanfaatkan Power Relation (Relasi Kuasa) dan Kondisi Psikis serta Medis dari Korban untuk melakukan tindakan melawan hukum, maka telah terjadi Pelanggaran terhadap prinsip Non-Maleficence (Prinsip Tidak Membahayakan Pasien) yang fundamental dalam praktik kesehatan. Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan etik dalam profesi yang mengharuskan perlindungan menyeluruh terhadap martabat manusia.
Lebih mengkhawatirkan, pengungkapan kasus ini tidak berasal dari sistem Whistleblowing (Mekanisme Pelaporan Internal Oleh Pihak Yang Mengetahui Pelanggaran) institusional yang seharusnya dirancang untuk mendeteksi potensi pelanggaran, tetapi justru dari media sosial, yang menandakan lemahnya mekanisme Early Detection (Deteksi Dini) dan Internal Compliance (Kepatuhan Terhadap Aturan Internal Organisasi).
Dalam perspektif hukum, hal ini menimbulkan pertanyaan besar terhadap efektivitas sistem Ethical And Criminal Accountability System (Sistem Pertanggungjawaban Etik Dan Pidana) dalam ruang profesional yang mestinya menjunjung tinggi integritas. Sementara dari sisi medis, penggunaan zat seperti midazolam tanpa indikasi klinis dan tanpa pengawasan jelas merupakan bentuk Professional Negligence In Medical Care (Malpraktik) yang merusak prinsip Informed Consent (Persetujuan Pasien Berdasarkan Pemahaman Yang Cukup Terhadap Tindakan Medis) dan membahayakan nyawa serta martabat pasien.
Oleh karena itu, penting untuk menghadirkan respons ilmiah dan sistematis terhadap kejadian ini. Tulisan "5 SOLUSI" yang saya tulis ini menjadi bentuk konkret dari refleksi multidisipliner untuk membangun sistem pencegahan yang lebih kuat, berbasis pada asas Restorative Justice (Keadilan Yang Memulihkan Hak Korban Dan Memperbaiki Pelaku), serta perlindungan yang komprehensif terhadap korban. Melalui pendekatan yang integratif antara hukum dan kesehatan, artikel ini berusaha menjawab kebutuhan mendesak akan rekonstruksi tata kelola kelembagaan yang menjunjung tinggi Access To Justice (Akses Terhadap Keadilan) dan menjamin Patient Safety (Keselamatan Pasien) secara berkelanjutan.
1. Reformasi Tata Kelola Etik Profesi Kesehatan
Diperlukan Penataan Ulang Regulasi dan Pengawasan Etik Profesi (Professional Ethical Governance Reform) dengan mengacu pada prinsip rule of law dan due process dalam penegakan etik kedokteran. Hal ini dapat diimplementasikan melalui pembentukan Dewan Etik Independen yang bersifat kuasi-yudisial, memiliki kewenangan tidak hanya administratif, tetapi juga investigatif, serta otoritas pengawasan etik secara real-time terhadap tenaga kesehatan, khususnya dalam ruang perawatan intensif dan situasi rentan.
Secara normatif, solusi ini berakar pada Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas rasa aman serta bebas dari ancaman kekerasan, dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, khususnya Pasal 51 huruf C, yang mewajibkan dokter menghormati hak pasien, serta Pasal 53 yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran disiplin.
Namun, realitas menunjukkan bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) masih bersifat reaktif dan terbatas pada aspek administratif, tanpa akses langsung ke mekanisme audit etik real-time atau investigasi independen. Oleh karena itu, model tata kelola etik kesehatan di Indonesia perlu meniru Health and Care Professions Council (HCPC) di Inggris atau Medical Board of California (MBC) di Amerika Serikat, yang memiliki otoritas penyelidikan etik langsung, bekerja sama dengan penegak hukum, serta menjamin transparansi proses etik melalui publikasi hasil pemeriksaan dan sanksi.
Selain itu, penerapan teknologi seperti Electronic Ethical Tracking System yang dikembangkan di Jerman untuk memantau interaksi dokter-pasien dalam sistem tertutup, dapat menjadi salah satu alat pengawasan berbasis teknologi etika preventif (Preventive Ethical Surveillance Technology), yang terbukti mengurangi laporan pelanggaran etik secara signifikan dalam 3 tahun terakhir. Upaya ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan profesi (Abuse Of Professional Power), khususnya terhadap pasien atau keluarga pasien yang berada dalam kondisi lemah secara fisik maupun psikologis, seperti yang lazim terjadi dalam ruang isolasi atau ICU.
2. Penguatan Sistem Perlindungan Hukum Bagi Korban
Negara harus mengoptimalkan mekanisme perlindungan hukum berbasis korban dan memperkuat mekanisme Victim-Oriented Legal Protection Mechanisms, agar tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan martabat dan keadilan restoratif bagi korban. Implementasi ini perlu melibatkan pendirian Unit Perlindungan Korban di setiap fasilitas layanan kesehatan, yang menyediakan layanan hukum, psikologis, dan medis secara terpadu dan gratis, terutama dalam kasus kekerasan seksual.
Prinsip Non-Victimization (Pencegahan Reviktimisasi Dalam Proses Hukum) menjadi asas penting, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya Pasal 67–70, yang mengatur hak korban untuk mendapatkan pendampingan hukum dan pemulihan psikososial tanpa syarat pembuktian awal.
Namun, dalam praktiknya, belum semua rumah sakit memiliki Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang aktif dan bersinergi dengan aparat penegak hukum dan lembaga bantuan hukum. Oleh karena itu, Indonesia dapat belajar dari sistem di Belanda yang memiliki pusat krisis Centrum Seksueel Geweld, yang memberi pertolongan pertama hukum dan psikologis dalam 24 jam pertama kejadian, atau dari Korea Selatan yang menerapkan sistem One-Stop Service Centers bagi korban kekerasan seksual. Langkah ini sekaligus mengimplementasikan prinsip Access To Justice (akses keadilan) dan Due Care In Healthcare Legal Practice (tanggung jawab hukum dalam pelayanan kesehatan) yang menjamin perlindungan korban dari awal pelaporan hingga tahap rehabilitasi.
3. Integrasi Kurikulum Anti-Kekerasan Seksual dalam Pendidikan Profesi Kesehatan
Kurikulum pendidikan profesi kesehatan di Indonesia perlu diintegrasikan secara wajib dengan pendidikan etik berbasis gender dan kesadaran hukum (Gender-Based Legal And Ethical Curriculum) sebagai bagian dari tanggung jawab profesi dalam membentuk karakter tenaga medis yang berintegritas.
Kurikulum ini harus menekankan prinsip Respect For Autonomy (penghormatan terhadap otonomi pasien), sebagaimana diatur dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengakui hak pasien untuk menentukan sendiri keputusan medisnya. Pendidikan anti-kekerasan juga wajib mencakup pemahaman hukum pidana, hukum etik kedokteran, serta materi tentang relasi kuasa (Power Relations) dalam praktik klinis.
Negara dapat mengambil contoh dari Australia, di mana Medical Board of Australia mewajibkan modul pelatihan etik berbasis gender dalam program pendidikan dokter dan perawat. Demikian pula Kanada, yang menyertakan Mandatory Consent & Sexual Boundary Training pada semua program medis sejak tahun 2016. Tujuan utama kurikulum ini adalah menciptakan tenaga medis dengan sensitivitas etik tinggi dan Zero Tolerance terhadap kekerasan seksual (Zero Tolerance Policy Toward Sexual Misconduct) dalam seluruh aspek praktik profesional mereka.
4. Digitalisasi Pengawasan dan Transparansi Ruang Medis
Untuk mencegah praktik kekerasan seksual dan pelanggaran etik di fasilitas layanan kesehatan, perlu dilakukan digitalisasi sistem pengawasan ruang medis dengan menempatkan kamera pengawas (CCTV) di zona-zona rawan seperti ruang isolasi, ruang pemeriksaan tertutup, atau area rawat inap yang memiliki resiko tinggi terjadinya penyalahgunaan wewenang medis (Zones Of Ethical Vulnerability). Teknologi ini berfungsi sebagai alat Digital Forensic And Preventive Tool (alat forensik digital dan pencegah pelanggaran), guna memperkuat akuntabilitas dan penegakan kode etik profesi kesehatan.
Namun demikian, penggunaan sistem pengawasan harus tetap mematuhi prinsip kerahasiaan dan privasi medis pasien (Medical Privacy Policy), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 48 dan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32, yang menekankan pentingnya menjaga informasi medis pasien.
Sebagai contoh, Inggris melalui National Health Service (NHS) telah menerapkan sistem CCTV di ruang pasien resiko tinggi dengan protokol privasi yang ketat. Jepang juga menerapkan pengawasan elektronik dengan sensor suara dan citra pada ruang perawatan lansia dan pasien disabilitas untuk mencegah kekerasan dan pelecehan. Kebijakan ini tidak hanya bersifat represif, melainkan juga membangun budaya transparansi medis (Medical Transparency) dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan.
5. Penerapan Model Restorative Justice dan Pemulihan Korban
Penyelesaian kasus kekerasan seksual dalam dunia medis tidak cukup hanya melalui jalur pidana. Negara dan institusi kesehatan perlu mengembangkan forum pemulihan berbasis Restorative Justice Forum (forum keadilan restoratif) untuk memberikan ruang dialog, penyembuhan, dan rekonsiliasi secara sukarela. Pendekatan ini penting untuk menjamin bahwa korban tidak hanya mendapatkan keadilan formal, tetapi juga keadilan emosional, sosial, dan spiritual (Emotional, Social, And Spiritual Reparation).
Model ini dapat mencakup mediasi antara korban dan pelaku, pernyataan maaf terbuka, kompensasi psikososial, dan pemulihan nama baik, dengan tetap menghormati hak otonomi korban (Victim’s Autonomy Rights) dan tanpa menghilangkan kemungkinan proses pidana.
Prinsip Restorative Justice ini telah tercermin dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dan beberapa Surat Edaran Kejaksaan Agung, serta dalam UU TPKS Pasal 6 ayat (2) yang menyebutkan pentingnya pemulihan berbasis trauma.
Di Kanada, sistem Restorative Justice Circles telah diterapkan dalam kasus pelanggaran etik di rumah sakit komunitas, dan di Selandia Baru, praktik Family Group Conference memungkinkan keluarga korban dan pelaku berdialog dalam suasana aman dan berbasis pemulihan. Penerapan model ini sekaligus menegaskan pendekatan Comprehensive And Humanistic Legal Health Approach (pendekatan hukum kesehatan yang komprehensif dan humanistik), sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial dan perlindungan korban dalam hukum modern.
Editor: (Nug/Humas) Gambar: Ilustrasi


Rektor UIN Surakarta : Fix, Pendaftaran UM-PTKIN Diperpanjang !
2 hari yang lalu - Umum
Juru Kunci 9 Besar, UIN Surakarta : Harapannya Bergerak Naik
3 hari yang lalu - Umum